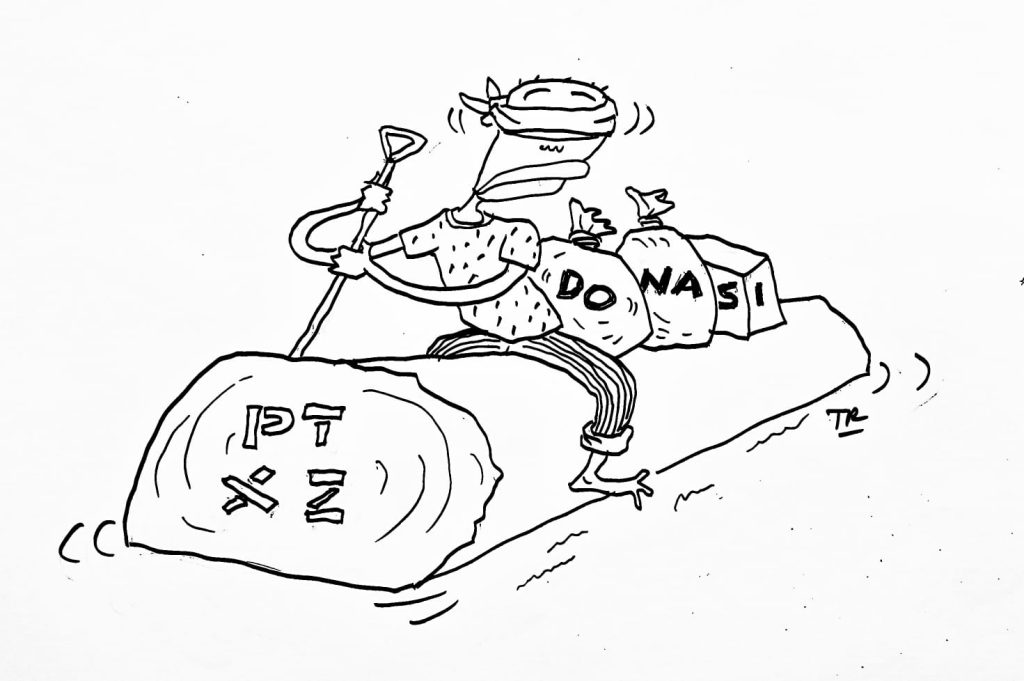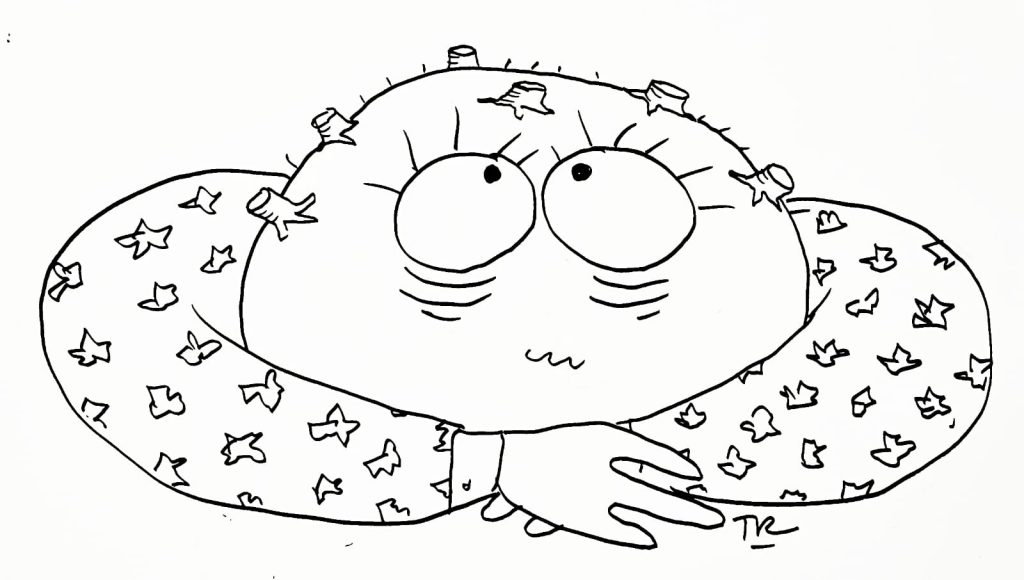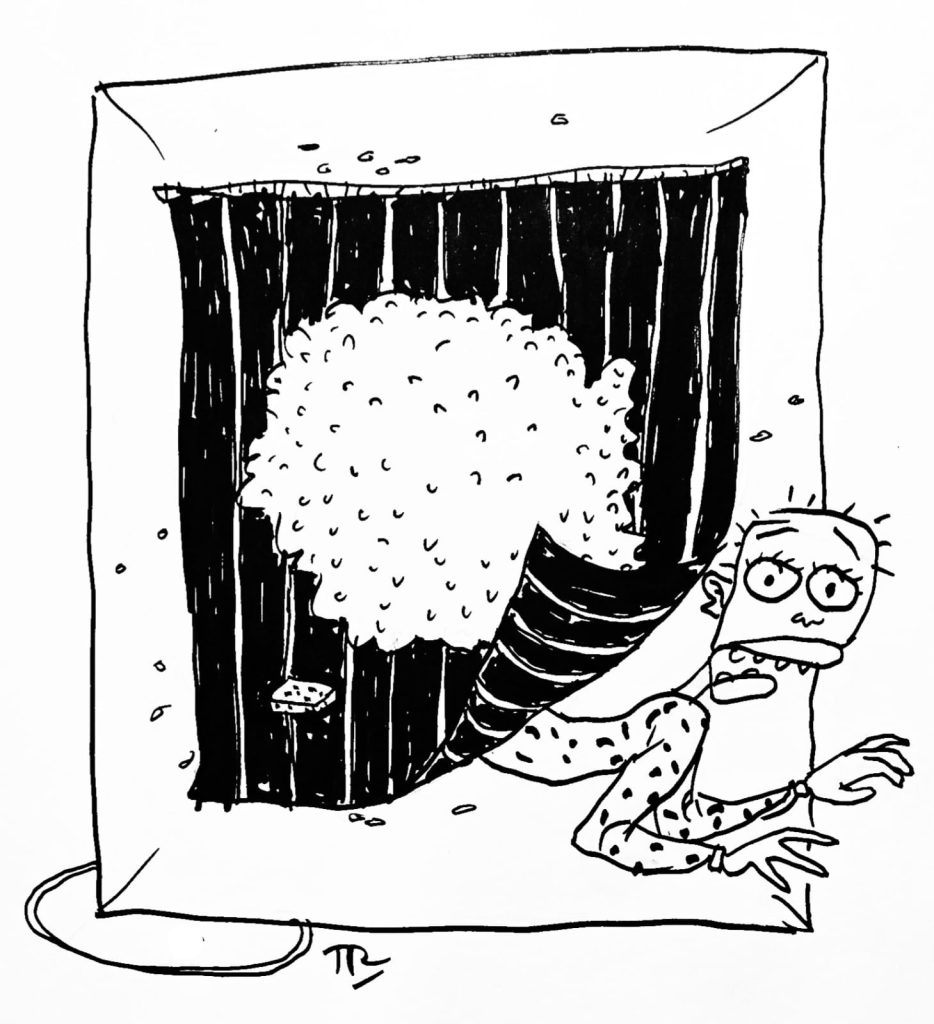NOVEMBER 2025, Pandji Pragiwaksono dituduh menghina adat pemakaman Toraja, Rambu Solo, dari klip komedinya yang sudah berdebu, tapi masih berambut (lihat perbedaan rambutnya sekarang)—12 tahun lalu. Tahun 2022, komika lain Raim Laode dilaporkan atas leluconnya yang melecehkan Sinonggi, makanan khas Suku Tolaki. Solusi berkomedi yang “aman” ternyata tidak sesepele “menertawakan etnis sendiri”. Soalnya 2020 lalu, Boris Bokir harus minta maaf secara terbuka setelah disomasi kantor-kantor pengacara. Materi yang ia bawakan beberapa tahun sebelumnya, dipermasalahkan karena merendahkan Suku Batak—padahal ia sendiri Batak.
Secuplik contoh di atas dalam lima tahun terakhir membentuk pola menarik: komedi yang mencatut identitas suku rentan jadi isu. Apakah benar komedi berbau kesukuan cuma membawa mudarat?
Memang sensitif Komedi sering dicap sepele. Namun, begitu menyinggung SARA—suku, agama, ras, dan antargolongan, mendadak ia naik kasta jadi headline nasional. Agama, yang resminya cuma enam saja, sudah beberapa kali bikin komedian kita terpeleset, apalagi suku. Baca juga: Lembaga Fobia Tawa Badan Pusat Statistik di tahun 2020 mencatat ada lebih dari 1.200 suku bangsa di Indonesia. Wajarlah kalau lanskap komedi kita jadi menantang, penuh “ranjau” sensitivitas. Itu belum termasuk komedi yang menyinggung kelompok di luar keagamaan dan kesukuan: gender, kelas sosial, preferensi politik, dan sebagainya. Jelas enggak mungkin mengulas semuanya dalam sebuah artikel saja. Minimal, harus jadi satu ensiklopedia khusus tentang humor berisiko di Indonesia, tuh! Masalahnya, tidak mungkin kita mencerabut topik etika dalam komedi. Sebab, seperti etika, humor—yang merupakan esensi dari komedi—hidup di ranah personal sekaligus sosial. Mari kita kunjungi pendapat Steven Benko, profesor kajian etika Meredith College, dalam pembukaan Ethics in Comedy: Essays on Crossing the Line (2020, h.3-6). Etika dibentuk oleh budaya, agama, hingga pengalaman hidup yang tiap individu miliki. Begitu pula humor. Apa yang seseorang rasa boleh dan tidak boleh ditertawakan sifatnya relatif—bergantung sekali pada hal-hal yang membentuk kepribadian masing-masing orang. Misalnya, ada orang yang bisa menertawakan lelucon stereotipikal tentang sukunya sebagai bentuk penerimaan diri, bahkan coping mechanism (tak ada yang bisa memilih dilahirkan jadi suku apa, bukan?). Namun, orang lain dari suku yang sama enggan melakukannya. Pasalnya, menertawakan lelucon itu setara mempermalukan martabat leluhurnya. Intinya, satu lelucon yang sama, bisa memancing dua reaksi berbeda: tawa geli atau somasi. Mengapa demikian? Karena sense of humor seseorang itu bergantung dengan apa yang filsuf Amerika Serikat Robert C. Roberts sebut sebagai perspectivity—keragaman sudut pandang. Orang dengan selera humor yang tinggi sebenarnya bukan orang yang mampu menertawakan atau membercandai apa saja, tetapi orang yang punya keragaman perspektif. Dalam praktiknya, ia bisa menggunakan sudut pandang yang pas untuk membingkai humor-humor yang etis maupun yang nir. Baca juga: Mahalnya Lidah Dengan mengaplikasikan perspectivity, kita bisa masuk ke fase moral holiday. Kita semua, menurut perspektif Roberts, berhak mengambil “cuti moral” sesekali. Libur sebentar saja dari kebiasaan menilai dunia dengan kacamata benar-salah yang kaku. Lewat apa? Menertawakan humor-humor yang tak sejalan dengan etika yang kita pegang. Sebab, menertawakan humor niretis bukan berarti kita kehilangan atau menurunkan standar moral kita. Kita cuma memberinya libur demi bisa melihat sisi lain dari realita. Harapannya, ketika kita tahu konsumsi humor termasuk moral holiday, kita bisa terhindar dari mobilisasi berbasis politik identitas. Dimobilisasi? Namun di sisi lain, humor tidak pernah murni personal. Ia juga bersifat komunal. Superiority theory datang dari kenikmatan menertawakan orang lain yang statusnya ada di bawah kita. Incongruity theory menggambarkan bagaimana humor bisa bikin orang saling klik ketika pikirannya sama-sama menemukan keanehan. Sementara itu, relief theory bicara tentang betapa mengekangnya norma sosial, hukum negara, atau nilai adat yang berlaku. Makanya kita bisa tertawa ketika ada humor yang menertawakan sistem kontrol itu karena sejenak kita terbebas dari “penjara” itu (secara psikologis). Semua penjelasan dari teori tersebut dirangkum oleh filsuf Henri Bergson sebagai berikut: “Kita selalu tertawa dalam kelompok.” Tawa bisa membentuk batas “kita” dan “mereka” (in/out group). Masalahnya, in/out group ini kerap kali disimplifikasi jadi politik identitas. Baca juga: Membaca Emosi Sandra Dewi dalam Kasus Harvey Moeis Di titik inilah, komedi yang mencatut kesukuan menjadi tambang konflik yang empuk. Polanya pun hampir selalu sama: catut komedi yang membahas suatu suku, bikin mereka tersinggung, lalu gerakkan representasi kolektifnya. Ke depannya, komedian bisa saja terus memilih jalan pragmatis: lompati saja ranjau-ranjau sensitivitas macam kesukuan itu kalau mau lebih aman. Namun, siap-siap saja, karena tiap humor pada dasarnya akan selalu membelah kerumunan. Pasti akan lahir kelompok orang yang tertawa dan marah, baik yang organik ataupun dimobilisasi, akibat suatu lelucon.
Di sisi lain, bagi para konsumen komedi, jangan ragu untuk mengambil moral holiday. Biar kita juga bisa memberi jarak agar tidak langsung terjebak dalam pusaran politik identitas. Toh, kita juga harus tetap menjaga fokus dan energi untuk mengawal isu-isu yang sangat krusial, seperti mafia hukum, perdagangan orang/anak, serta korupsi uang kita semua—para pembayar pajak.